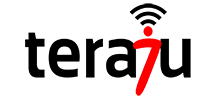Baru saja saya membeli rumah. Tak mewah, cukup sederhana, tetapi sudah lebih dari cukup untuk keluarga kecil saya. Ini seperti pencapaian besar setelah bertahun-tahun kerja keras: akhirnya memiliki tempat yang layak disebut “rumah sendiri”. Tapi tahukah Anda? Yang bersukacita bukan hanya saya dan keluarga. Negara pun ikut berpesta.
Sebab, ada “biaya syukuran” wajib yang harus dibayarkan ke negara: pajak. Dalam transaksi jual beli rumah, dua jenis pajak langsung muncul:
- PPh (Pajak Penghasilan) – Dibayar penjual: 2,5% × Rp800.000.000 = Rp20 juta.
- BPHTB (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan) – Dibayar pembeli: 5% × (Rp800.000.000 – Rp60.000.000) = 5% × Rp740.000.000 = Rp37 juta.
Total pajak: Rp57 juta.
Bayangkan: Setelah bertahun-tahun kerja keras, menabung, mencari rumah, dan berjuang mengatur cicilan, begitu transaksi selesai… negara langsung “panen” Rp57 juta. Tanpa bantuan mencari rumah. Tanpa bantuan renovasi. Tanpa bantuan mencicil KPR.
Apa sudah cukup? Belum. Masih ada biaya balik nama, akta jual beli, notaris, dan lain-lain yang bisa mencapai Rp6–11 juta. Belum lagi biaya tambahan lainnya.
Akhirnya saya sadar: yang perlu dibenahi bukan hanya cara membayar, tapi cara bernegara. Sebab, satu hal tak bisa dilupakan: negara tak pernah benar-benar hadir saat rakyat kesulitan memiliki hunian layak. Tapi negara selalu siap hadir—saat waktunya menarik pajak dari rakyat yang akhirnya bisa punya rumah.
Usulan Saya:
- Pembeli rumah di bawah Rp500 juta bebas pajak selama 10 tahun pertama kepemilikan.
- Pengembang didorong untuk berkembang, rakyat sejahtera, negara pun tetap senang.
(Peter Gontha, pengusaha kawakan)