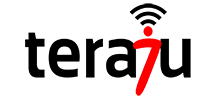Oleh: Yusriadi
Saya sering ditanya orang, “Siapa calon yang ‘kita’ pilih dalam Pemilu dan Pilpres 2019 ini?” Sering juga saya “ditembak”, “Kamu sih… sudah pasti pilih calon nomor….”
Termasuk Sabtu (9/2) kemarin. Saat konyen –kunjungan lebaran Imlek ke rumah keluarga, saya juga mendapat pertanyaan yang kurang lebih sama.
Saya dipancing dengan pertanyaan, “Mana enak Yus, zaman SBY atau zaman Jokowi?”
Tentu, sebagai pribadi dan jamiyah saya sudah punya pilihan. Tetapi, saya tidak ingin menyampaikan pilihan saya pada orang yang belum saya tahu posisinya. Apalagi dalam suasana lebaran.
Jika pilihannya sama, mungkin tidak ada masalah. Pilihan sama akan membuat suasana menjadi lebih baik. Tetapi, kalau pilihan berbeda, suasana pertemuan mungkin akan lain. Paling tidak, suasana akan sedikit rusak karena masing-masing mungkin akan mempertahankan argumentasi atas pilihan, dan mungkin saja pihak yang lain berkeberatan atau tidak setuju dengan argumentasi itu.
Lihat saja apa yang terjadi di ruang publik dan media sosial hari ini. Silang pendapat meruncing menjadi saling serang. Parahnya, serangan-serangan sudah masuk ke wilayah pribadi, yang di sana ada ghibah dan fitnah. Dosa-dosa sepertinya sudah tidak dipikirkan lagi oleh mereka-mereka itu. Padahal persoalannya sederhana: pilihan berbeda dan diberitahukan plus mengajak orang lain –tersurat atau pun tersirat, untuk memilih yang sama.
Jadi, dalam situasi sekarang ini, saya pikir, lebih baik diam saja dan mendengar. Prinsipnya, ‘Diam itu emas’.
Ternyata, pilihan sikap saya itu benar. Dalam percakapan kami selanjutnya, banyak hal yang terungkap berdasarkan pengalaman lapangan beliau. Sebagai orang dagang, yang berkali-kali mengatakan tidak suka politik — setahu saya beliau memang tidak pernah ikut dalam kegiatan politik praktis—memiliki banyak informasi yang baru.
Beliau membandingkan susah-senangnya bergerak. Susah senangnya merentasi jalan ke pedalaman. Susah senangnya berdagang. Susah senangnya mendapatkan barang. Susah senangnya berurusan.
Beliau bandingkan prosedur dan pelaksanaannya. Beliau bandingkan perasaan yang timbul dan dirasakan.
Akhirnya, beliau berkesimpulan, “Sekarang tuh, kami, saya-lah, nyaman-nyaman sakit”. Di sana sini ada nyaman atau enak dan disukai, tetapi di sana juga ada tidak nyaman atau sakit.
Enak dan tidak enak itu merupakan konsekuensi dari apa pun kebijakan. Beliau mafhum, kebijakan tertentu diambil pada level tertentu. Ada level presiden, gubernur, walikota-bupati, bahkan ada level RT. Beliau juga menyadari, apa yang dikeluhkan bukan berarti salah kebijakan. Untuk alasan tertentu, seperti kebijakan tidak boleh pungli, dimaksudkan agar tata kehidupan menjadi lebih baik.
Lalu, akhirnya, berkaitan dengan pertanyaan di awal, siapa yang akan dipilih, dengan gaya khasnya beliau meyakini calon tertentu –disebutkan namanya, akan menang.
“Orang ‘kan menilai. Kalau pun dipengaruhi, ya… berapalah… Saya berani tarohan,” katanya mantap.
Kecuali tentang tarohan, saya setuju pada cara berpikir beliau. Masyarakat kita jumlahnya sangat banyak dan yang banyak itu bermacam-macam. Ada yang kadang memang emosional, ada juga yang pragmatis, dalam menentukan pilihan. Mereka ini bisa menyantap propaganda dan hoaks dengan nikmat.
Tetapi, di tengah kita juga masih banyak orang yang baik. Orang baik ini pilihannya pasti didasarkan pada pertimbangan kebaikan. Mereka tidak akan termakan oleh hoaks bagaimana pun gencarnya karena mereka masih memiliki mata hati dan mata batin. Pada dan bersama merekalah kita menaruh harapan.
Maka, jawaban atas pertanyaan di awal tulisan ini adalah, “Saya akan memilih calon yang terbaik. Saya memilih pilihan orang yang baik”. (*)