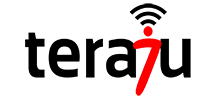Oleh: Ambaryani
Kerukunan harus dijaga. Kebersamaan mesti dipelihara. Apa lagi di wilayah yang pernah terlibat konflik. Itulah kearifan masyarakat di Sidodadi, Sepantai, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat. Warisan yang diamalkan hari ini.
-o-
“Kita singgah lebaran ke rumah Mbah Sukito!”
Tiba-tiba Mae mengajak kami mampir ke rumah bercat hijau putih di depan kami. Tanpa menunggu jawaban kami, beliau sudah berjalan ke arah rumah itu.
Hari itu, tahun 2018 lalu, kami dalam perjalanan pulang dari rumah Wo Ru, setelah lebaran idul fitri di sana. Sebenarnya, kali ini kami –Mae, saya, suami dan anak, berlebaran ke rumah paman. Jadwal kunjungan ke rumah tetangga, nanti, diselesaikan Mae dan Pae, setelah kami kembali ke Pontianak. Waktu kami agak singkat di kampung karena libur tidak lama.
Suami saya terlihat keheranan. Dia tahu rumah siapa yang akan dikunjungi. Selama ini saya dan keluarga memang belum menceritakan tentang lebaran berbeda di Sepantai ini.
Suami berasal dari daerah lain nun jauh di hulu, dan baru kali ini mengikuti kami lebaran di kampung ini. Sejak menikah, kami tidak berkesempatan lebaran di sini karena lebih memilih lebaran di Pontianak saja.
Kali ini, kami diberikan kemudahan bisa berlebaran di kampung halaman di Sepantai, hulu Sungai Sambas.
“Kok, lebaran ke sini. Memangnya ..?” Suami berbisik pada saya. Tetapi, Mae yang berjalan di depan mendengarnya.
“Lihatlah sendiri… Biar kamu tahu,” Mae tersenyum.
Sekarang saya paham maksud Mae. Lebaran ke rumah Mbah Sukito ini untuk memberikan informasi kepada menantunya.
“Mbah…” Mae memanggil.
“Yo…”
Terdengar sahutan di dalam rumah, di lantai bawah. Mbah Tumi, istri Mbah Sukito mempersilakan kami masuk. Lantai bawah, bagian dapur rumah ini memang lebih dekat ke tangga.
Kami naik ke rumah berlantai dua. Ada tangga luas seperti di gedung-gedung di kota, yang langsung terhubung dengan ruang tamu di lantai atas. Desain ini memang unik dan hanya milik paten Mbah Sukito di kampung ini.
Ruang tamu bercat biru. Di dinding terpasang foto keluarga. Ada salib besar dengan hiasan bunga. Sebuah tanda yang sangat jelas mengenai agama pemilik rumah. Di tengah ruangan ada meja rendah, di atasnya berbagai jenis kue dan minuman.
Mbah Sukito dan kemudian istrinya keluar dari lantai di pojok ruangan –tangga, menyambut kami dengan ramah. Kami bersalaman. Tidak ada ucapan “selamat lebaran” seperti lazimnya. Semua memang maklum.
Sudah menjadi tradisi di sini lebaran saling mengunjungi. Itu hal yang biasa dilakukan di mana-mana.
Tetapi, sebenarnya apa yang terjadi di sini cukup menarik. Orang di kampung ini saling mengunjungi, termasuk yang bukan beragama Islam.
Mbah Sukito beragama Protestan. Beliau satu di antar belasan warga di sini yang beragama Protestan. Sementara di kampung Sidodadi ini mayoritas beragama Islam.
Sebagai muslim, lebaran adalah tradisi yang dimeriahkan. Setiap rumah membuka pintu untuk menerima kunjungan tetangga. Tuan rumah menyediakan kue dan minuman yang disediakan untuk tamu yang datang. Termasuk yang bukan Islam, seperti Mbah Sukito sekeluarga.
Menurut Mbah Sukito, tradisi ini mereka lakukan karena dalam keluarganya, multi agama; Islam dan Protestan. Mereka ikut lebaran karena keluarga dan tetangganya ada yang beragama Islam. Selain itu, Mbah Sukito salah satu sesepuh di kampung. Rumah sesepuh sering dikunjungi semua orang. Dan, ini menjadi salah satu kearifan Mbah Sukito dalam menjaga kebersamaan dan kerukunan.
Pak Muri, tokoh masyarakat Sidodadi yang ditemui awal Juni 2020, mengatakan perbedaan suku dan bahasa ada sejak wilayah kampung ini pertama kali ditempati, sekitar tahun 1983. Kala itu, orang dengan latar belakang suku, bahasa dan agama berbeda membaur dalam program transmigrasi. Sebagian besar orang Jawa, Sunda, dan Melayu lokal yang disisipkan.
Dalam perkembangannya kemudian, penduduk trans berkurang karena sebagian tidak betah di lokasi. Ada yang pindah lokasi, ada yang balik kampung asal.
Seiring perjalanan waktu, keadaan mulai “membaik” dan stabil karena lahan dan pemasaran mulai bersahabat dengan warga trans. Lalu, penduduk bertambah satu dua karena pernikahan dengan orang luar komunitas, dan kelahiran. Hingga, pada hari ini (tahun 2020) di kampung Sidodadi ini ada orang Jawa, Sunda, Melayu, Madura, dan Dayak.

Bahasa Jawa kasar menjadi bahasa utama di sini. Tetapi, bahasa Melayu (Sambas) dan bahasa Indonesia juga mendapat tempat. Begitu pun dengan bahasa Sunda.
Di beberapa jalur, orang Jawa sangat biasa menggunakan dua atau tiga bahasa. Mereka bisa menukar penggunaan bahasa sesuai lawan bicara dan konteks. Ada penyesuaian.
Modal sosial, gotong royong dan kebersamaan tertanam kuat di tengah masyarakat. Budaya “Rewang” menjadi pengikat dan modal berharga. Setiap keluarga yang menyelenggarakan hajatan, pasti akan dibantu oleh warga.
Saya mendapatkan foto (seperti yang di atas) yang memperlihatkan kebersamaan warga saat rewang. Ada bagian membersihkan bahan, menyiapkan bumbu, memasak, dan mendekorasi tenda. Semuanya ambil bagian.
Ada juga warga yang membantu secara materi. Bantuan seperti ini dicatat. Mereka –setiap keluarga, memiliki buku catatan sumbangan yang mereka terima saat perkawinan, dan atau sunatan anak lelaki. Kelak, apabila tetangga menyelenggarakan hajatan, mereka akan membalas sumbangan materi.
“Kalau tidak ikut, yo… tak enak,” kata Pak Muri.
Mae juga mengatakan hal senada. Ada konsekuensi atau sanksi moral jika seseorang abai pada kebersamaan itu.
“Kalau sering tidak ikut, bisa kena kucilkan orang nanti”.
Sumbangan materi juga terjadi saat pembangunan rumah. Sudah biasa, jika ada seseorang yang akan membangun rumah, tetangga –terutama keluarga yang lain, menawarkan bantuan; entah itu dalam bentuk semen, atap seng, dan lainnya.Tambahan lagi, warung selalu bersedia memberikan talangan untuk bantuan itu.
“Maka, kalau mau membuat rumah, agak gampang,” ujar Lek Rin, seorang warga yang ditemui di rumahnya. Dia menyebutkan beberapa buah rumah yang dibangun baru, dalam beberapa bulan lalu.
Gotong royong insidentil juga ada. Bila ada orang yang sakit agak berat warga menyumbang untuk biaya berobat. Selain itu, sebelum ada jalan darat dan sepeda motor, warga menolong menggotong si sakit hingga sampai di dermaga perahu motor, di Sungai Sambas.
Kebersamaan dalam masyarakat bisa juga dilihat dari kegiatan ekonomi. Kelompok kerja sudah dibentuk sejak dahulu. Menggarap ladang bersama. Sekarang kelompok itu menjadi menjadi kelompok tani (Pok-Tan), khusus untuk koperasi sawit, menggantikan kelompok kerja ladang padi yang sudah hilang.
Ada tiga kelompok koperasi sawit di sini. Kelompok ini dibentuk berdasarkan wilayah kerja atau wilayah usaha. Tidak ada kaitan dengan asal turunan, suku atau agama. Sifatnya pragmatis.
Mereka membentuk koperasi seiring kebutuhan penjualan buah sawit. Dalam kelompok ini, panen sawit diatur bergantian, agar memudahkan penimbangan dan pengangkutan.
Mugi, beragama Protestan, suku Jawa, menjadi ketua untuk kelompok tani salah satu wilayah hamparan (hamparan kulon). Dia mengurus dan mengatur banyak hal. Mulai dari harga, pencatatan, hingga pemotongan.
Anggota kelompok tani yang beragama Islam memiliki cukup banyak potongan di koperasi sawit ini. Ada potongan untuk simpanan koperasi, iuran jalan, potongan zakat, arisan kurban, sumbangan masjid, bayar pupuk dan bibit. Semua itu merupakan bentuk kebersamaan.
Kebersamaan warga pernah mendapat ujian berat saat kerusuhan 1997. Kala itu kerusuhan melibatkan dua kelompok suku. Di kampung ini, kala itu ada beberapa orang dari kalangan suku yang terlibat. Mereka yang berasal dari suku ini dilindungi oleh warga. Jiwanya ditolong, harta bendanya dijaga. Oleh sebab itu, tidak ada pertumpahan darah dan kerusakan harta benda dalam peristiwa besar di Kalbar di sini. Orang dari suku tersebut sebagian kemudian pindah, dan saat itu atau pada kesempatan lain dapat menjual harta benda mereka.
Ketika covid-19 melanda, warga Sidodadi dengan cepat mereaksinya. Begitu ada instruksi pemerintah soal social distancing dan pembatasan, pengurus desa membatasi orang keluar masuk dan kegiatan berkumpul. Percaya tak percaya, warga mematuhi perintah pengurus desa.
“Pokok e.. apa kata pemimpin, semua orang patuh,” kata Mae.
Pak De Yitno, dalam percakapan kami malam itu, awal Juni 2020 juga menegaskan hal yang sama. Mereka tidak menunggu ada orang di kampung yang sakit atau meninggal karena Covid-19, baru percaya. “Kita harus taat kepada pemimpin, pemimpin yang benar”.
Warga di dusun hulu Sambas ini belajar banyak dari pengalaman hidup mereka di kampung terpencil di tanah baru. Pengalaman hidup itu diambil dari kerusuhan tahun 1997, yang bermula dari Sanggau Ledo, Bengkayang. Jarak Sanggau Ledo hanya 1,5 jam naik motor dari sini. Kelompok yang melakukan sweeping terhadap orang dari suku tertentu, sampai juga ke dusun ini.
Lalu, tahun 1999 kerusuhan Sambas terjadi. Sambas adalah ibu kota kabupaten Sambas. Tempat yang menjadi pusat bagi orang orang Sambas, termasuk Sidodadi ini. Suasana tegang dan mencekam sampai juga ke kampung ini untuk beberapa pekan. Konflik di sekitar mengepung mereka untuk sekian lama.
Dalam situasi tegang dan kacau, modal sosial terasa sangat membantu mendamaikan dan menenangkan hati. Kebersamaan membantu mereka mengatasi persoalan yang muncul. Ketaatan pada pemimpin mengomandoi mereka bergerak bersama dan kompak.
Loyalitas pada pemimpin dan kelompok terus dijaga dan dirawat. Sikap ini membuat mereka dapat mengedepankan kepentingan umum, tanpa melihat atau terbatas oleh identitas suku dan agama. (Ambaryani, Kontributor https://teraju.id/ )