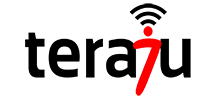Oleh: Eka Hendry Ar
Akhir-akhir ini penulis merasa serba salah dan nyaris kehabisan akal untuk berwacana. Termasuk untuk membincangkan isu-isu aktual yang terjadi di ruang publik. Alasannya pertama, terus terang ada “rasa takut”, kalau-kalau salah (atau keseleo kata) sehingga ada delik untuk dipidanakan. Kedua, “Kesulitan” menentukan sikap, seperti simalakama. Barangkali juga kurang pas kalau dibilang kesulitan, karena lebih dikarenakan stigma apriori terhadap situasi yang terjadi. Dimana para pihak dengan mudah menuduh kalau kita berpendapat A, berarti pro kelompok ini. Sebaliknya, berendapat B, dituduh pro kelompok itu. Sehingga ada teman yang berujar, “Aku speechless dengan kondisi hari ini.
Memang idealnya, bisa saja kita mengabaikan imej demikian. Seperti pepatah “anjing mengonggong, kafilah berlalu”. Namun karena kita hidup dalam ruang yang sama, menjadi inteligensia atau cendikia, yang benar-benar berjarak dari kepentingan pragmatis terasa sulit. Sehingga kita mulai merasa risih dengan atmosfir yang “pengap” ini. Seolah-olah kita tersandera dan sekaligus terdakwa oleh penilaian publik yang riuh rendah dengan “polusi” hujat menghujat.
Semuanya sibuk bersuara, menyederhanakan kompleksitas pikiran dan idealisme, seakan hanya dalam demarkasi standar episteme-nya masing-masing.
Episteme adalah istilah Michel Foucault bermakna kaca mata yang digunakan masyarakat untuk menilai realitas, termasuk menjadi kriteria kebenaran versi yang menggunakannya. Sementara semua realitas sudah terpolarisasi ke dalam posisi biner (berhadap-hadapan), hitam putih, benar salah. Jika tidak satu kepentingan, maka berarti lawan.
Jadi episteme kebenarannya adalah kepentingan masing-masing pihak. Sehingga kebenaran kehilangan esensinya, menjadi berhala. Kebenaran bukan diuji sebagai pengetahuan atau berdasarkan standar etis dan estetis, akan tetapi menjadi sebatas ideologis. Sehingga narasinya, menjadi ajang klaim mengklaim dan yang paling lantang dan digjaya hegemoninya (via perang buzzer).
Banyak yang “wafat” dalam pertarungan wacana (istilah Foucault untuk medan pembicaraan, diskusi dan polemik guna meneguhkan hegemoni) yang demikian. Matinya kebenaran (death of truth), matinya kepakaran (death of expertise) dan matinya kehanggatan berbangsa (death of happines).
Pertama, kematian kebenaran, sebab kebenaran tidak lagi lahir sebagai objektivitas berpikir atau proses berpengetahuan, melainkan hanya sebatas klaim kebenaran. Kalau sudah sedemikian rupa, bagaimana mungkin dapat menerima kemungkinan kebenaran pada pihak lain. Ruang kompromi yang menjadi jiwa eksistensi bangsa ini, lambat laun akan pupus.
Kedua, kematian kepakaran. Ini istilah dari Tom Nichols dalam bukunya The Death of Expertise, yang coba penulis adaptasi dalam konteks mutakhir Indonesia. Karena setiap orang sudah merasa dirinya paling pandai dan paling benar, maka dengan jumawanya ia mendalilkan kebenaran semata dalam sudut pandang dan kepentingannya. Suara-suara para cerdik pandai tidak lagi didengar dan menjadi rujukan, terlebih lagi jika yang bersangkutan telah dipetakan sebagai pro kelompok lain. Semua orang larut dalam euforia “kebebasan saling mencaci maki”.
Pada akhirnya kita sama-sama terperangkap dalam labirin pengap yang kita ciptakan sendiri. Lambat laun mengakibatkan kekurangan “oksigen” untuk bernafas dalam kegembiraan dan kehangatan berbangsa dan bernegara.
Mau tidak mau, kita harus menarik jarak dulu dari ruang yang demikian. Untuk mendapatkan suplai “oksigen” demi bertahan dalam waktu yang lama. Suplai “oksigen” berbangsa ini bisa kita ambil atau gali lagi dari sari pati (atau protein) Pancasila.
Pandangan dunia dan ideologi bangsa, yang mengikat segala keragaman negeri ini dalam satu komitmen bersama. Kemana Pancasila yang menjadi modal ampuh kita selama ini? Hilangkah eksistensinya dalam jiwa berbangsa kita? Ataukah ia ikut mati, bersama matinya kebenaran, matinya kepakaran dan matinya kebahagian berbangsa?
Tentu ini adalah pertanyaan reflektif, untuk menginggatkan kita semua. Bahwa ada cita-cita besar kita berbangsa, lebih besar dari sekedar perebutan “kekuasaan”, yang sunatullahnya pasti timbul tenggelam.
Yaitu cita-cita besar kita untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.
PR bangsa ini masih banyak, termasuk memastikan apa yang menjadi amanah UUD 1945 itu menjadi kenyataan.(Penulis adalah Dosen IAIN Pontianak)