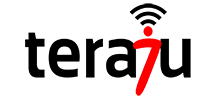Oleh: Beni Sulastiyo
Pak Sutarmidji, Gubernur Kalbar baru saja melaporkan seorang pelajar kepada pihak kepolisian. Pak Sutarmidji tampaknya kesal karena ulah bandel satu di antara 6 juta rakyatnya.
Menurut berita, warga yang ia laporkan adalah seorang pelajar yang masih duduk di kelas 2 SMU. Pelajar itu dituduh telah berkata kasar terhadap Pak Gubernur, saat berorasi di tengah aksi demonstrasi yang menolak UU Cipta Kerja.
Bandel sekali. Tapi saya yakin anak itu masih anak yang cerdas! Hahaa.
Karena tak terima dengan sikap sang pelajar, Pak Gubernur melaporkannya kepada Polisi.
Menurut saya, sikap seorang gubernur yang marah terhadap warganya, bahkan melaporkannya ke polisi itu adalah sebuah kewajaran. Wajar, karena hal itu sudah sesuai dengan falsafah kehidupan demokrasi “al-barati” yang dianut oleh negeri ini. 🙂
Mengapa wajar?
Karena dalam falsafah masyarakat “albarati”, gubernur adalah penguasa. Sesuai dengan arti kata dari bahasa asalnya: governador”, (Portugis), “gobernador” (Spanyol), atau.. “gouverneur” (Belanda) yang artinya sama saja, yaitu penguasa.
Posisi penguasa itu pastilah orang yang paling berkuasa. Paling berkuasa di antara rakyatnya. Maka, semua orang harus menghormatinya.
Jadi, jangan samakan gubernur dengan seorang kiai dalam dunia kepesantrenan. Jangan over estimate kitanya. Gubernur itu bukan ayahmu, bukan ayah kita! 🙂
**
Dalam dunia pesantren, Kiai itu bukan penguasa walau posisinya sama dengan gubernur, pejabat tertinggi di wilayahnya. Akan tetapi seorang kiai bagaikan seorang ayah bagi para santrinya.
Seorang kiai adalah seorang pengasuh.
Istilah pengasuh ini digunakan di pesantren karena warga pesantren, yaitu para santri, sejatinya adalah anak-anak asuh Kiai. Karena tugas utamanya adalah mengasuh, maka seorang kiai di pesantren seringkali disebut “pengasuh”.
Di negara kita, Gubernur adalah jabatan tertinggi di sebuah provinsi. Jabatan itu adalah jabatan yang bersifat politis. Hubungan antara gubernur dan warga adalah hubungan antara penguasa dengan hamba (orang yang dikuasai).
Sementara dalam dunia kepesantrenan, hubungan kiai dengan santri adalah seperti hubungan antara ayah dan anak. Landasannya kasih sayang.
Dalam budaya nusantara, nilai dasar kepengasuhan adalah kasih sayang. Makanya seorang ayah atau ibu yang sedang menjaga anaknya sering diungkapkan dengan kalimat, “ia sedang mengasuh anaknya”. Dan bukan “ia sedang menguasai anaknya”.
Karena basis falsafahnya adalah kasih dan sayang, maka seorang ayah atau seorang seorang ibu tak mungkin baper kepada anak yang diasuhnya, sekalipun anaknya bersikap tidak wajar. Misalnya minta susu di tengah malam, nangis-nangis saat kita sedang sibuk bekerja, bahkan mem-pipis-kan atau meng-eek-kan baju kita, saat kita sedang menggendongnya. Tak boleh baper!
Kalau baper, kalau merajuk dengan anaknya sendiri, ayah atau ibu itu malah justru akan menjadi aneh. Ayah kok baperan, ibu kok merajukan. Hahaa.
Demikian juga seorang kiai. Seorang kiai memandang para santri sebagai anaknya sendiri. Hubungan antar keduanya adalah seperti hubungan orang tua dengan anaknya, didasari oleh kasih dan sayang.
Di kampung-kampung, santri-santri asuhan para Kiai banyak yang bandel. Siang mengaji, sore main judi. Sore mengaji, malamnya menjaga tempat prostitusi.
Namun, para kiai jarang yang baper saat mengasuh santri-santri bandel seperti ini. Para santri tetap diasuh, mereka tetap dianggap seperti anaknya sendiri. Para santri akan terus dibimbing, sembari berharap mudah-mudahan suatu saat kelak, para santri bandel itu akan berubah menjadi manusia yang lebih baik.
Di beberapa tempat, sering pula ada santri yang nakalnya ekstrem banget. Ada yang mengejek, bahkan memfitah kiainya. Tapi kiai-kiai yang diperlakukan seperti itu tak lantas baper. Mereka justru mendoakan anak-anak asuhnya yang bermasalah itu.
Para kiai sadar, kalau ia ikut-ikutan mengejek saat diejek, kalau ia ikut-ikutan memfitnah saat difitnah, maka derajat kekiaiannya, derajat kepemimpinannya bukan justru naik, tapi malah turun.
Kan lucu jika seorang ayah yang dipipisin atau dieekin anaknya, lalu marah dan balas mipisin anaknya juga hahaa. Atau setelah balas mipisin dilanjutkan dengan melaporkan anaknya sendiri ke Polisi dengan delik pencemaran baju baik. Hahaa.
Ayah yang bersikap aneh seperti ini tentu akan dianggap sebagai ayah yang tak normal. Sikap ayah seperti itu juga akan membuat kita yang menyaksikanya menjadi bingung, “kok ayahnya yang jadi kekanak-kanakan? Jadi sebenanrnya mana ayah, mana anak yak? Hahaa.
Sementara jika seorang Gubernur yang melaporkan anaknya sendiri ke Polisi, ya wajar. Karena Gubernur itu kan PENGUASA. Walaupun tetap saja ada keanehannya.
Aneh… karena yang memilih ia menjadi penguasa adalah warganya. Tapi setelah jadi penguasa, kok malah kita yang justru dikuasainya, kok malah kita yang diperintahnya, kok malah kita yang dipaksa-paksa untuk menghormatinya. Haha.
Padahal dalam ajaran demokrasi, katanya rakyatlah yang berkuasa, rakyatlah yang memerintah, rakyatlah yang harus dihormati? Gimana sih? Haha.
Makanya, sampai sekarang saya seringkali bingung dengan praktik demokrasi yang diimpor dari orang-orang barat di negeri ini.
Harusnya rakyat yang giat melaporkan pemimpinnya. Sekarang malah pemimpin yang giat melaporkan rakyatnya.
Demokrasi bikin mumet! Blunder. Ga jelas! Hahaa.
Jadi pengasuh sajalah!
Jogja, 12.11.2020
Beni Sulastiyo
Santripenikmatkupi