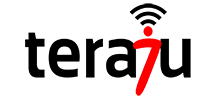Oleh Hermayani Putera
Alam dan budaya bagi masyarakat Dayak di Kalimantan tempatku bekerja adalah satu kesatuan, ibarat dua sisi dari koin. Keduanya saling bersisian, saling mengisi, dan saling menegaskan. Upaya melestarikan hutan dan menyejahterakan masyarakat harus diletakkan dalam perspektif melestarikan adat dan budaya.
Dalam prakteknya, hubungan erat antara alam dan budaya masih bisa aku saksikan dalam beberapa kesempatan menghadiri acara adat beberapa kelompok masyarakat di tempatku bekerja. Selalu ada ritual ketika mulai musim berladang agar terhindar dari berbagai gangguan hama penyakit tanaman ataupun ketika selesai panen sebagai bentuk syukur. Hal ini biasanya diekspresikan dalam upacara adat di kampung, seperti Dange pada masyarakat Dayak Kayaan di DAS Mendalam, atau Niki’ Benih pada masyarakat Iban di sekitar lintas utara Kapuas Hulu, dan Pamole’ Beo’ Banuaka di kelompok masyarakat Tamambaloh.
Di kalangan masyarakat Dayak Taman juga upacara sejenis ini, dinamakan Mandung. Ekspresinya berbeda dan beragam sesuai tradisi dan adat masing-masing kelompok masyarakat Dayak. Namun ada yang bisa ditarik sebagai benang merah: menjaga harmoni manusia dan alam melalui serangkaian upacara adat.
Rangkaian upacara adat ini berlangsung meriah dengan tetap menjaga kesakralan, dan umumnya berlangsung selama beberapa hari. Persiapan dilakukan berbulan-bulan sebelumnya. Panitia dibentuk untuk mengkonsolidasikan segenap potensi sumber daya yang ada di kelompok masyarakat tersebut maupun pihak lain di luar mereka. Tarian digelar, makanan dan minuman khas lokal pun disajikan sebagai bentuk penghormatan kepada tokoh adat, masyarakat, dan tamu undangan lainnya yang hadir.
Karena kami sangat dekat dengan masyarakat, hampir setiap ada gawai atau acara adat ini, WWF selalu diundang. Dalam setiap gawai ini, ada satu sesi yang sulit dihindari, yakni minum tuak. Minuman tradisional masyarakat Dayak ini biasanya diolah dari beras ketan (pulut).
Caranya, beras pulut atau ketan ini direndam air selama sekitar dua minggu. Selain menghasilkan air minuman, beras yang direndam dengan cara fermentasi atau peragian ini juga akan berubah bentuk menjadi tapai.
Bahan lain membuat minuman tuak adalah air nira yang berasal dari sadapan tongkol bunga atau mayang pohon enau atau nipah. Mayang dari enau atau nipah ini dipotong atau disadap, dan air manis yang menetes keluar dari tandan yang dipotong tersebut kemudian ditampung dalam wadah dari bambu ataupun jirigen plastik. Air nira hasil tampungan yang belum mengalami fermentasi tidak mempunyai kadar alkohol. Aku biasanya memesan air nira yang masih baru ini jika ke lapangan. Rasanya segar.
Yang lebih banyak disajikan dalam acara adat adalah air nira yang telah mengalami fermentasi selama beberapa hari dan kandungan gula yang ada di dalam air nira tersebut berubah menjadi alkohol dengan kadar sekitar 4%.
Di sinilah tantangannya. Sebagai seorang muslim, aku harus taat karena ajaran Islam melarang minuman jenis apapun yang mengandung alkohol. Tapi di sisi lain, undangan menghadiri acara adat ini juga perlu dihargai mengingat posisiku sebagai wakil dari organisasi WWF yang bekerja bersama masyarakat. Menghadiri undangan acara adat adalah bentuk penghormatan dan penghargaan tersebut.
Beberapa kali aku bisa menolak secara halus untuk tidak minum, mengikuti saran Hermas, Zulkifli, atau Lasah, teman di WWF yang biasanya menemaniku menghadiri acara adat ini. “Abang tegaskan saja kepada panitia bahwa Abang muslim. Tegaskan juga kalau Abang sedang kurang sehat dan sudah minum obat sebelum datang ke acara,” begitu saran mereka bertiga. info minum obat ini tentu saja harus sedikit berbohong, he he he.
Cara ini cukup berhasil, karena sebagian besar panitia sangat menghormati dan menjunjung tinggi toleransi atas perbedaan agama dan keyakinan di antara kami. Mereka respek begitu tahu aku seorang muslim. Perlakuan yang sama mereka terapkan juga kepada para tamu lainnya yang muslim.
Namun satu pengalaman pergi ke suatu acara ketika mengantarkan tamu dari Jakarta memberikan pelajaran baru bagiku. Pada bagian penerimaan tamu, panitia yang masih muda dan mendapat tugas menyajikan minuman tuak sebagai sajian pembuka kepada tamu yang hadir, memaksaku untuk minum tuak. Walaupun sudah kukatakan bahwa aku seorang muslim, mereka tetap berkeras. Syukurlah waktu itu ada Zulkifli yang membawa mobil mengantar kami ke acara tersebut. Zul menawarkan kepada panitia untuk meminum segelas tuak yang semula disajikan untukku. Beres, ada solusinya untuk saat itu.
Dalam perjalanan pulang aku lalu berpikir, harus ada solusi setiap menghadiri acara adat di tempat lain agar tidak terjadi ketegangan seperti yang baru saja aku alami. Ini berpotensi bisa merusak acara yang sakral bagi masyarakat tersebut. Ketika singgah ke pasar Putussibau mendampingi tamu membeli oleh-oleh sebelum mereka kembali ke Jakarta, terlihat olehku jejeran botol sirup. Aha. Warna sirup rasa leci itu yang membuatku tersenyum lebar, karena mirip sekali dengan warna minuam tuak.
“Wah, benar juga Bang. Abang bisa bawa sirup leci ini kalau kita menghadiri acara adat. Nanti saya yang atur, kalau pas giliran Bang Herma yang disuguhkan minuman tuak, bisa pakai sirup ini. Tuak rasa leci ya Bang,” kata Zul, sambil tertawa di mobil yang membawa kami ke Bandara Pang Suma Putussibau, mengantar para tamu kami terbang ke Pontianak.
Dua botol sirup rasa leci aku simpan di kantor. Beberapa minggu kemudian, undangan menghadiri acara adat kembali datang ke kantor. Kali ini aku tidak perlu lagi berbohong minum obat kepada panitia untuk menghindari minuman tuak.
Begitu pula untuk perjalanan lapangan seperti membawa donor ke berbagai lokasi kerja WWF, yang kadang-kadang kami juga disuguhkan acara adat dan minuman tuak. Aku tetap mengikuti prosesi adat dengan tenang, karena sudah ada solusinya: tuak rasa leci.
Salam Lestari, Salam Literasi
#MenjagaJantungKalimantan, #KMOIndonesia, #KMOBatch25, #Sarkat, #Day20, #hermainside, #SalamLestariSalamLiterasi