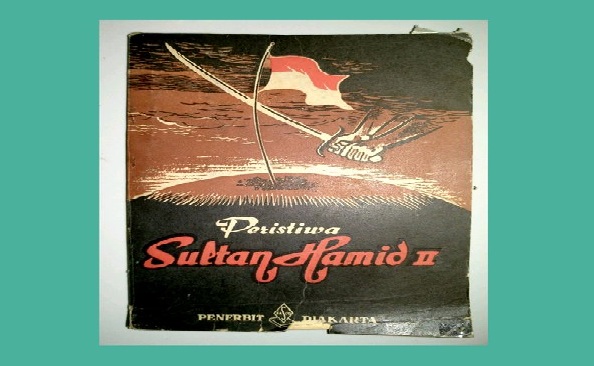Oleh: Nur Iskandar
Dalam ilmu jurnalistik praktis penentuan cover buku sama dengan penentuan halaman 1 surat kabar. Antara judul dengan gambar mesti menarik. Karena menarik maka laku dijual. Karena laku dijual, maka bisnis media bisa bertahan.
Bisnis media memang unik. Dia tidak seperti bisnis kebanyakan. Jualannya informasi, sementara informasi adalah komoditi yang cepat basi. Koran khususnya–maka koran gulung tikar satu persatu di era kesejagatan kini. Termasuk buku–tapi buku gudang ilmu–masih bisa bertahan karena sifatnya yang mudah dipegang dan tidak melelahkan mata akibat frekuensi atau efek gradasi warna layar atawa screen.
Judul buku terbitan 1953 dan 1955 sama, namun gambarnya berbeda. Ilmu jurnalistik menilainya tidak lagi pada judul, tetapi pada pesan gambar yang “menarik” sehingga laku dijual.
Cover terbitan 1953–persis di tahun putusan MA dijatuhkan kepada Sultan Hamid bergambar gelas tinta dengan pena berbulu elang. Pena dan tinta ini lazim menjadi gambar yang memesankan literasi atau pencatatan. Kita dapat memahaminya sebagai catatan atas kasus Sultan Hamid II dengan isi memang demikian adanya. Ada sembilan bagian isi buku tersebut mulai dari pengantar, latar belakang, tuntutan, pembelaan dan akhirnya putusan. Benar-benar catatan persidangan.
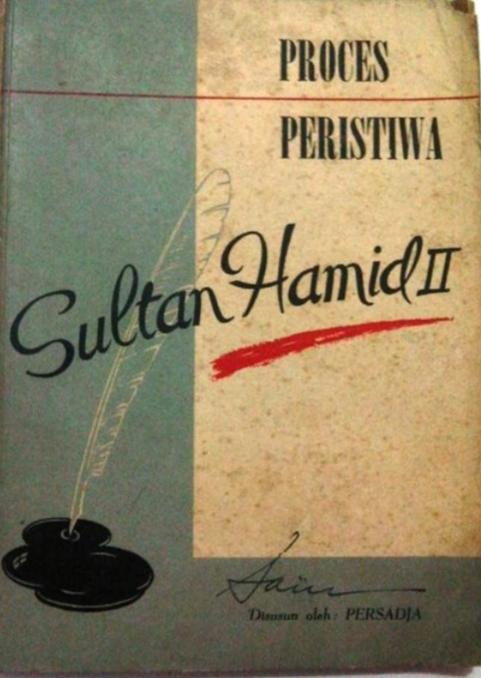
Menjadi menarik adalah buku kedua. Gambarnya bendera merah putih dengan tiang masih kurus kerempeng pertanda lemah betul sehingga ditiup angin pun bisa tumbang, lalu ada tangan perkasa menghunus pedang dan mengancam tegaknya sang merah putih. Pesannya tajam–setajam pedang–hendak merobohkan merah putih di atas bumi pertiwi.
Cocokkah gambar itu dengan isinya? Ini menariknya menakwil makna cover tersebut sesuai ilmu jurnalistik yang mengandung 5W+1H. Misalnya siapa yang menggambar cover tersebut. Siapa yang pesan? Apakah ada desain gambar sampul lainnya yang diajukan? Siapa yang memutuskan dari Penerbit Persatuan Djaksa? Apakah Djaksa Agung? Apakah Mahkamah Agung? Menarik juga bahwa buku ini tak ada tersebut sesiapa tim penulisnya….Alhasil banyak pertanyaan masih menjadi misteri dan misteri itu bisa disibak dari investigasi untuk bahasa pers-nya dan riset menurut kaidah akademisnya. Untuk menyibak misteri Hamid II yang mengaku federalis sejati–100% vs isi sidang di mana jaksa menyebutkan dengan kata “kita” kepada saksi Menhan Hamingkubuwono IX yang mohon maaf banyak lupanya itu di persidangan, padahal umurnya baru 41 tahun ketika itu menyibak misteri prejudice atau syakwasangka. Padahal prejudice atau syakwasangka dalam ilmu jurnalistik amat sangat diharamkan. Misalnya prejudice bahwa suku tertentu adalah busuk hati dan lekas marah. Itu tidak boleh demikian. Begitupula pada haluan federalis vs unitaris. Saya mengutip kata “prasangka” mengutip dari isi persidangan di mana Menhan “menyangka-nyangka” saja bahwa Hamid bla-bla-bla. Baca selengkapnya buku Peristiwa Sultan Hamid bagian tanya jawab hakim dan jaksa kepada saksi-saksi.
Generasi muda pecinta sejarah dan pegiat literasi boleh menindak-lanjuti ladang riset di bidang desain gravis, ilmu jurnalistik, termasuk tata-negara berbalut hukum dan politik ini. Sungguh menarik untuk menerangkan duduk soal Negara Republik Indonesia yang saat itu sudah merdeka 5 tahun. Membaca “tinta-pena berbulu elang” dan atau “pedang tajam menghunus tiang bendera merah putih di ibu pertiwi* sesungguhnya sudah dapat diketahui siapa sesungguhnya pahlawan dan pengkhianat sebenarnya.
Alternatif akademik lainnya yang menarik adalah bedah buku. Bedah buku ini di prodi-prodi sejarah. Saya bersedia bicara lewat laporan-laporan jurnalistik dan ilmu jurnalistik yang saya dalami sesuai ketentuan Kode Etik Jurnalistik maupun UU Pers No 40 tahun 1999. * (Penulis adalah Pimred teraju.id / 08125710225–WA)